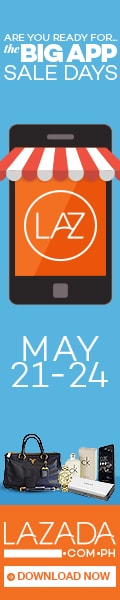(MonitorSultra.com) — Sebuah tulisan singkat dari sepucuk surat untuk ibunya, tulisan yang tak rapi yang mengindikasikan ia masih anak kecil namun dipaksa untuk dewasa oleh keadaan. Memang tindakannya tak dibolehkan, namun itulah jalan akhir agar tak memberikan beban dan kesedihan yang berkepanjangan untuk sang ibu.
Seorang anak yang memilih mengakhiri hidupnya dengan tragis, di desa kecil bernama Nenowea Nusa Tenggara Timur. Di bawah pohon cengkeh la tergantung dengan seutas tali yang telah memutus napas dan harapan besarnya. Sebab buku dan pena seharga sepuluh ribu rupiah (Rp10.000) yang tak mampu dijangkaunya menjadi perenggut hidupnya.
Sepuluh ribu adalah nominal kecil bagi mereka yang hidup glamor di perkotaan, angka yang hanya cukup untuk biaya parkir di pusat perbelanjaan di kota besar. Tapi angka inilah yang tak mampu menjadi jalan untuk meraih cita-cita seorang anak SD di NTT sehingga bunuh diri adalah tindakan yang ia ambil, angka kecil yang menjadi vonis hidup-matinya.
Tragedi ini bukan sekedar cerita pilu keluarga miskin, ini adalah dakwaan moral terhadap negara. Ketika penguasa republik ini gemar berpidato tentang Indonesia emas di masa datang, bonus demografi, dan investasi triliunan. Mirisnya, masih ada anak yang merasa hidupnya tak lagi berarti hanya karena tak mampu membeli alat tulis. Sebuah realitas yang menampar wajah penguasa jauh lebih keras dari pada kritik politik mana pun.
Di saat yang sama, negara sibuk membahas rencana dukungan dana bagi Dewan Perdamaian Gaza serta menggelontorkan dana yang tak terhitung digitnya oleh kalkulator untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dua agenda yang dibungkus dengan niat mulia. Solidaritas kemanusiaan global dan peningkatan kualitas generasi muda. Namun, dengan tragedi anak bunuh diri di NTT memaksa kita untuk bertanya dengan sinis, untuk siapa sesungguhnya negara bekerja?
Kita tak menampikan pentingnya solidaritas moral untuk Palestina. Empati internasional adalah sikap yang terhormat. Tetapi satu hal harus diingat, solidaritas sejatinya harus dimulai dari rumah sendiri. Tampil dermawan di muka dunia menjadi paradoks tersendiri jika halaman belakang masih ada anak-anak dengan napas tersengal dan putus asah karena kemiskinan. 16,7 triliun rupiah adalah angka fantastis untuk anak-anak bangsa ini yang berkeringat meraih masa depannya namun secara sukarela diberi untuk orang lain. Membantu gaza adalah pilihan moral. Menyelamatkan anak Indonesia adalah kewajiban konstitusional.
Kasus anak bunuh diri di NTT membuka secara telanjang bagaimana bobroknya kebijakan sosial negeri ini. Pendidikan gratis, perlindungan sosial berjalan. Namun semua itu hanya di atas kertas semata. Nyatanya di lapangan, seorang anak mati hanya karena orang tuanya tak punya uang untuk membeli buku dan pena seharga sepuluh ribu.
Menjadi jawaban sederhana, bahwa sistem kita prematur. Bantuan tak tepat sasaran, birokrasi kita terlalu rumit bak benang yang kusut dan pemerintah terlalu jauh dari kenyataan rakyat kecil. Negara hanya sekedar hadir di baliho dan spanduk dengan segala pernyataan indah namun utopis dalam fakta. Ungkapan capaian hanya sekedar ilusi bagi rakyat yang tak terjamah mata penguasa.
Dana 335 triliun di hamburkan untuk sebuah program ambisius pemilik kuasa negeri. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menguras dompet negara menjadi janggal jika dilihat dari kacamata tragedi ini. Negara seolah lupa bahwa pendidikan bukan soal makan, bukan soal gizi semata, nagara lupa soal akses paling dasar dalam pendidikan. Anak-anak butuh buku, butuh alat tulis, butuh seragam, butuh kepastian sekolah. Selama masih ada anak yang tak bisa belajar karena tak punya buku dan pena, semua program besar terdengar seperti lelucon.
Anak-anak memang butuh makan, tapi apalah arti perut kenyang jika tas sekolah tetap kosong, atau bahkan tak mempunyai tas?
Tragedi bunuh dirinya anak SD di NTT sesungguhnya menampar narasi besar tentang Indonesia Emas 2045, bonus demografi, generasi unggul dan Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM). Semua jargon itu runtuh seketika ketika berhadapan dengan sebuah fakta yang ironis di sudut Nusantara bahwa masih ada anak yang kehilangan harapan bahkan nyawa hanya karena kemiskinan ekstrem.
Hal ini bukan hanya sekedar angka kemiskinan semata. Tapi ini soal martabat manusia.
Hilangnya nyawa seorang anak kecil yang gantung diri di pohon cengkeh di sebuah desa jauh dari Ibu Kota ini adalah alarm darurat bahwa prioritas negara yang salah arah, isi dompet negara seharusnya lebih dulu dikeluarkan untuk kebutuhan paling elementer rakyat terpenuhi sebelum dipakai untuk proyek megah atau program makan yang juga menguntungkan bagi segelintir orang (lihatlah bagaimana seorang anak dari wakil DPRD Sulsel yang mengelola 41 dapur MBG yang dapat meraut keuntungan ratusan juta dalam sehari) dan juga agenda-agenda internasional.
Yang dibutuhkan saat ini bukanlah ucapan bela sungkawa dari pejabat yang sekarang ini berseliweran di algoritma media sosial, melainkan tindakan nyata. Bantuan pendidikan langsung bagi anak miskin secara keseluruhan (seragam, buku, pena, akses sekolah dan fasilitas sekolah yang memadai).
Negara tidak boleh kalah oleh harga pena dan buku 10.000 rupiah. Jangan ada lagi ada anak yang merasa lebih baik mati dari pada menyusahkan orang tuanya.
Namun jika para penguasa negeri ini masih sibuk memoles citra diri lewat program raksasa sementara persoalan elementer tak tersentuh. Maka uang negara hanya sekedar menjadi angka-angka keluar yang tertera dalam dokumen tebal tanpa nurani. Juga, Indonesia tidak akan menjadi bangsa kecil jika tak menyumbang pada luar negeri, karena sesungguhnya Indonesia akan menjadi bangsa yang besar jika dapat memastikan setiap generasinya bisa sekolah dengan tanpa rasa takut.
Tragedi di NTT ini meninggalkan pertanyaan paling sederhana dan sekaligus menyakitkan. “Di mana negara ketika seorang anak membutuhkan buku dan pena seharga 10.000?” selama pertanyaan ini belum dapat terjawab dengan tindakan nyata, selama itu pula janji-janji kesejahteraan yang terpampang pada baliho, spanduk, pidato-pidato yang tersiar di media massa hanyalah sebuah kebohongan yang dipoles rapi.
Sepuluh ribu rupiah telah merenggut satu masa depan, semoga juga ia dapat merenggut kesombongan penguasa-penguasa negeri yang sudah lama abai terhadap jeritan tangis rakyatnya sendiri.
(Tim Redaksi).